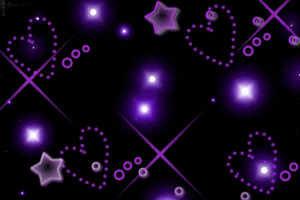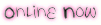Oleh Kang Kolis
Saya terpesona dengan wujudiyah, tertarik dan ingin mengkaji lebih serius. Mungkin akan saya mulakan daripada tinjauan sejarahnya di Nusantara dan hubungkait yang berlaku di dalamnya
Kajian tentang wujudiyah di Nusantara telah ramai dilakukan, khasnya di Indonesia dan Malaysia, tetapi setakat ini belum pernah ada kajian tentang wujudiyah yang membabitkan kedua-dua bangsa ini sekaligus,
apalagi berjaya menghuraikan hubung kait yang tersimpul antara kedua-duanya, sama ada yang bersifat intelektual keagamaan mahupun politik keagamaan. Kebanyakan kajian hanya bertumpu kepada biografi tokoh dan karakter ajaran wujudiyah yang dianjurkan oleh masing-masing sufi, tanpa ada upaya yang sungguh-sunguh untuk mengkaji lebih dalam tentang adanya keterkaitan dan komunikasi timbal balik di antara para tokoh yang dikaji juga implikasi terhadap pergerakan pemikiran Islam kontemporer dewasa ini.
Memahami hubungan antar aliran wujudiyah di Indonesia dan Malaysia adalah penting dalam kaitannya dengan perkembangan tasawuf di Nusantara, di samping alasan di atas, juga kerana kawasan ini secara geografis terletak pada pinggiran Dunia Muslim yang cenderung dilupakan oleh kebanyakan peneliti moden, justru kebudayaan Islam di sini tidaklah dicorakkan semata-mata oleh kebudayaan bangsa Arab, India, Turki, Parsi, atau Cina (Abdul Rauh Yaccob, 2007: 25). Faham keagamaan Islam di wilayah ini telah mengakar, tumbuh dan berkembang sesuai dengan nilai-nilai tempatan, sehingga dipercayai telah bercampur dengan budaya lokal.
Berasaskan data sejarah Islam di Nusantara, hubungan antara kaum Muslim di kedua-dua negara ini telah terjalin dengan erat sejak masa-masa awal Islam dan semakin meningkat apabila penindasan kolonial ke atas kaum Muslim semakin mengganas. Hubungan itu bermula dari pertemuan para tokoh intelektual dan agamawan Nusantara di Haramayn untuk menimba ilmu agama, fiqah, hadis, tasawuf dan lain-lain.
Bermula sebagai salah satu pusat perdagangan internasional, kerajaan-kerajaan Muslim di Nusantara telah mencapai taraf kemakmuran yang tinggi sehingga boleh memberikan kesempatan kepada segmen-segmen tertentu dalam masyarakat Muslim untuk melakukan perjalanan ke pusat-pusat keilmuan dan keagamaan di Timur Tengah. Ditambah lagi oleh upaya Dinasti Uthmani mengamankan jalur perjalanan haji membuat perjalanan naik haji dari Nusantara semakin baik. Apabila hubungan ekonomi, politik sosial keagamaan antar negara-negara Muslim di Nusantara dengan Timur Tengah semakin meningkat sejak abad ke-14 dan ke-15, maka kian banyak pulalah penuntut ilmu dan jemaah haji. Ini mendorong munculnya komuniti yang oleh sumber-sumber Arab disebut Asyhab al-Jawiyyin (saudara kita orang Jawi) di Haramayn.
Tentang asal-usul istilah jawi ini, masih menjadi tanda tanya, tapi pendapat yang muktabar bahawa ia berasal daripada jawa yang di-Arab-kan menjadi jaawah. Kata jaawah ini disebutkan oleh Marco Polo sebaai nama lama bagi kepulauan di Indonesia, termasuk Sumatera (Bandingkan dengan Hashim Musa, 199: 69-70). Namun, istilah jawi meskipun berasal daripada kata Jawa, mengandungi maksud setiap orang yang berasal dari Nusantara (Azra, 2004: 132).
Identiti Asyhab al-Jawi bagi pelajar Nusantara di Haramayn secara tidak langsung telah mengukuhkan perkumpulan mereka sebagai satu persaudaraan nation yang memiliki rasa tanggung jawab bersama baik selagi masih di Haramayn mahupun setibanya di Nusantara. Di antara meraka setelah menamatkan pengajian di Makah dan Madinah memilih untuk kembali ke tanah Jawi Malaysia atau Indonesia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan agamanya. Di sinilah selanjutnya mereka bekerjasama menjadi agen of change sekaligus transmitter utama tradisi Islam dari pusat-pusat keilmuan Islam di Timur Tengah ke Nusantara. Proses penyebaran ini dilakukan secara individu-individu dan atau melalui institusi-instiusi pondok (Lihat Fauzinnaim dalam Farid Mat Zain, 2007: 115-128).
Ajaran yang paling banyak ditransformasikan adalah fiqah dan tasawuf dengan warna dan cirikhas yang tentu berbeza antara masing-masing ajaran mengikut pemahaman, metode dan pengalaman pribadi penganjurnya. Dalam bidang tasawuf, selain fahaman tasawuf sunni di Nusantara juga diajarkan fahaman tasawuf wujudiyah yang sampai sekarang masih berkembang di sebahagian besar wilayah Indonesia, Malaysia dan Selatan Thailan. Antara ulama yang berjaya mentransmisikan ajaran yang dimaksud boleh disebutkan di sini adalah: Hamzah Fansuri dan muridnya Syamsuddin Sumatrani di Acheh, Ronggo Warsito dan Syekh Siti Jenar di Jawa, Haji Hasan Musthafa di Sunda, Muhammad Nafis al-Banjari di Kalimantan, dan lain-lain.
Patut dikemukakan bahawa para sufi yang disebutkan di atas seluruhnya memahami ajaran-ajaran wahdatul wujud atau wujudiyah-nya Ibn Arabi dan ajaran insan kamil-nya al-Jilli, dengan basis teori tanazzul dan tajalli. Teori-teori yang terkesan membawa phanteisme ini masuk ke Indonesia dan Malaysia khasnya melalui dua tokoh Aceh, Hamzah Fansuri dan Syamsuddin Sumatrani.
Selain pengaruh sufi Ibn Arabi dan al-Jilli, sufi asal India Muhammad Fadhullah al-Burhanfuri juga tak kalah pengaruhnya dalam mewarnai corak tasawuf di Malaysia dan Indonesia, terutama kerana buku Tuhfah karyanya yang masuk dan dipelajari oleh beberapa sufi di tanah Jawi. Al-Kurani berkisah sebagaimana yang dikutip oleh Azra:
Kami mendapat informasi yang dapat dipercaya dari kelompok (jama’ah) Jawiyyin bahwa telah tersebar di kalangan penduduk tanah-tanah Jawah beberapa buku mengenai haqiqah (realitas Ilahiah) dan pengetahuan makrifat (‘ulum al-asrar) yang disampaikan dari tangan ke tangan oleh orang-orang yang mempunyai pengetahuan dikarenakan telaah mereka sendiri dan ajar orang lain… Dikatakan (oleh kaum Jawiyin) itu kepada saya bahwa di antra buku-buku terkenal tersebut adalah sebuah ringkasan yang berjudul Al-Tuhfat Mursalah ila (Ruh) al-Nabi, Saw., yang ditulis oleh sang ahli dengan bantuan Tuhan, Syaikh Muhammad Ibn Syaikh Fadhi Allah al-Burhanfuri (Azra, 2004: 135)
Perpaduan antara konsep wujudiyah Ibn Arabi, insan kamil-nya al-Jilli, dengan Tuhfah-nya al-Burhanfuri melahirkan apa yang disebut dengan teori martabat tujuh. Teori ini tampak mewarnai wacana pemikiran sufi Nusantara. Hanya saja kemudian perlu dibezakan siapakah tokoh yang menganut bulat-bulat perpaduan pemikiran Ibn Arabi, al-Jilli dan al-Burhanfuri, serta siapa yang kemudian menolak fahaman ketiga-tiga sufi itu kemudian mengklaimnya sebagai fahaman wujudiyah mulhidah.
Ajaran martabat tujuh dan manunggaling kawulo gusti oleh sebahagian ahli diidentikkan dengan wahdatul wujud. Hal ini berdasarkan pemahaman bahawa khasnya tentang teori martabat tujuh, ternyata berhubung kait dengan paham tanazzul dan tajalli. Konsep martabat tujuh merupakan tingkatan-tingkatan perwujudan melalui tujuh martabat, yaitu ahadiyah, wahdah, wahidiyah, alam arwah, alam mitsal, alam ajsam dan alam insan. Para pembahas martabat tujuh di Pulau Jawa mengenal ungkapan “la dudu iku iya iki, sejatine iku iya” (bukan itu iya ini, sesungguhnya memang iya), yang artinya bahwa hakikat ini dan itu sama, itu-itu juga. Ungkapan ini, yang kemudian dalam istilah Sunda, Haji Hasan Musthafa, dikenal dengan ungkapannya “disebut aing da itu, disebut itu da aing” (apabila dikatakan aku kenyataannya itu; dan apabila dikatakan itu, kenyataannya aku) (M. Solihin, 2005: 193). Manakala wujudiyah Ibn Arabi juga mengatakan: “Maha Suci Dzat yang menciptakan segala sesuatu, dan Dia adalah segala sesuatu itu sendiri”. Oleh itu, berdasarkan ungkapan-ungkapan ini menurut al-Taftazani aliran ini pada dasarnya berasaskan tapak rasa (al-Taftazani, 2003: 201).
Kecenderungan yang mengarah kepada fahaman manunggal (union-mistik) itulah yang kemudian ditentang keras oleh para sufi sunni di Nusantara. Antara para sufi sunni ini adalah Nuruddin al-Raniri, Sayyid Alawi, dan lain-lain. Kemudian tokoh sufi yang sedikit berbeza dengan al-Raniri dan Alawi, adalah Abd. Shamad al-Palimbani, Abd. Rauf al-Sinkili, dan Muhammad Aidrus. Ketiga sufi yang disebutkan terakhir ini berpegang teguh kepada transendensi Tuhan, kendatipun secara sepiritual manusia boleh dekat (qurb) dengan Tuhan. Tetapi, ketiga-tiga sufi ini menggarisbawahi bahawa proses qurb ini tidak akan mengambil bentuk kesatuan wujud antara manusia dengan Tuhan. Dengan demikian ketiga-tiga sufi ini lebih moderat dalam memahami aliran wujudiyah atau martabat tujuh, sehingga ada yang menyebut aliran tasawuf mereka ini bercorak neo-sufisme (Lihat Azyumardi Azra, 2004: 335).
Sejarah wujudiyah di Nusantara begitu pelik dan unik justru apabila bertembung dengan doktrin syariah sebagaimana yang terjadi di Jawa pada kes yang melibatkan wali songo dengan syekh Siti Jenar tentang fahaman “manunggaling kawulo gusti”, di Banjar antara Haji Abd Hamid Abulung dengan Syekh Muhammad Arsyad, juga di Aceh ketika zaman al-Raniri ada perburuan dan pembunuhan terhadap pengikut aliran wujudiyah ini (lihat Azra, 2004: 350), dan kes lain yang tejadi di belahan bumi Nusantara. Namun wujudiyah yang tercabar ternyata begitu mengakar dalam tradisi masyarakat Jawi yang majoriti menganut akidah ahl al-Sunnah wa al-Jamaah aliran Ash’ari dan Maturidi (lihat, Abdul Syukor Haji Husin 1998: 7—9).
Akhir-akhir ini di Indonesia, tokoh-tokoh pembaruan Islam yang popular seperti Nurkholis Madjid dan tokoh pluralis lain juga para penganjur liberalisme Islam sering menjadikan Syekh al-Akbar Muhyiddin ibn Arabi sebagai guru filsafat mistik yang dihandalkan. Hal ini secara tidak langsung mereka dapat disebut sebagai fihak-fihak yang mewarisi serta menghidupkan aliran wujudiyah dengan corak yang lebih moden.